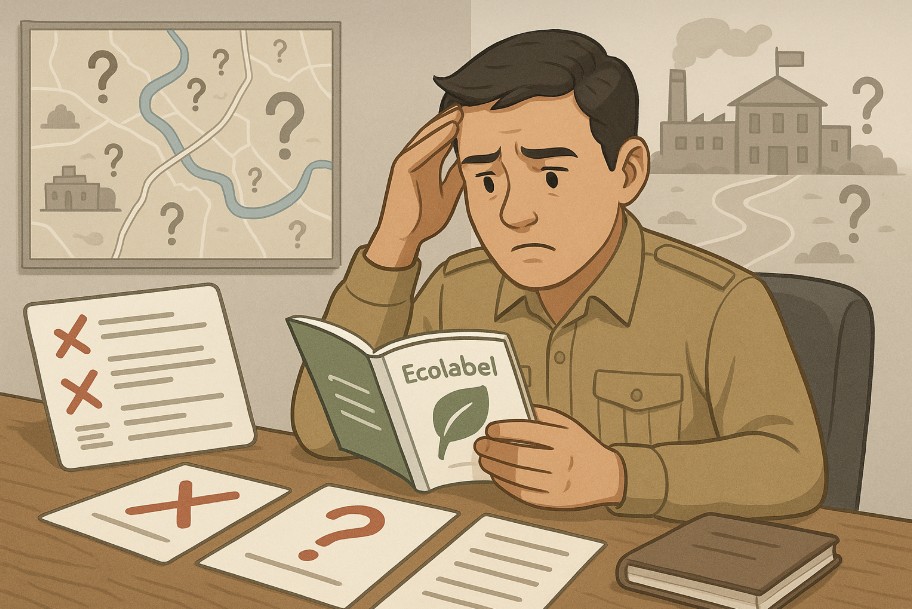I. Pendahuluan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) di tingkat daerah selama ini lebih dikenal sebagai proses administratif untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pembangunan infrastruktur. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan, istilah green procurement-yakni pengadaan ramah lingkungan yang memasukkan kriteria ekologi ke dalam setiap tahap proses pengadaan-menjadi semakin populer. Pada level pusat, sejumlah instrumen dan kebijakan sudah diterbitkan untuk mendorong green procurement, namun implementasinya di daerah menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan terintegrasi. Artikel ini akan mengulas secara mendalam berbagai kendala yang kerap muncul dalam pelaksanaan green procurement di daerah, baik yang bersifat struktural, kelembagaan, maupun teknis, serta memberikan rekomendasi solusi agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
II. Konsep dan Tujuan Green Procurement
Sebelum membahas kendala, perlu dipahami terlebih dahulu konsep green procurement. Green procurement adalah praktik pengadaan yang tidak hanya menilai harga, kualitas, dan waktu pengiriman, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari produk atau jasa yang dibeli. Tujuan utamanya meliputi:
- Reducing Environmental Impact
Mengurangi jejak karbon, penggunaan energi fosil, dan limbah berbahaya. - Promoting Sustainable Industries
Mendorong produsen dan distributor untuk menerapkan proses produksi ramah lingkungan. - Optimizing Total Cost of Ownership (TCO)
Memperhitungkan biaya operasional dan pengelolaan akhir siklus hidup produk, bukan hanya harga beli awal. - Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Kontribusi pada SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab), SDG 13 (Aksi Iklim), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan).
Ketika konsep ini diadopsi secara penuh, green procurement dapat menjadi instrumen kebijakan yang kuat untuk memadukan agenda ekonomi dan lingkungan, menciptakan sinergi antara penghematan anggaran publik dan perlindungan alam.
III. Pentingnya Implementasi Green Procurement di Daerah
Pemerintah daerah berperan strategis dalam implementasi green procurement karena mereka memiliki kendali langsung atas belanja operasional-mulai dari peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas, hingga proyek infrastruktur lokal. Kebijakan green procurement di daerah dapat:
- Menurunkan biaya jangka panjang melalui efisiensi energi dan perawatan.
- Menciptakan pasar lokal untuk produk hijau, sehingga memacu pertumbuhan UMKM dan industri berkelanjutan di wilayah tersebut.
- Meningkatkan citra dan kepercayaan publik, menunjukkan komitmen terhadap lingkungan dan pemerintahan yang bertanggung jawab.
- Mendukung agenda iklim nasional, karena emisi dari belanja pemerintah berkontribusi pada total emisi nasional.
Namun, pentingnya ini belum selalu diikuti dengan kesiapan dan kapasitas instansi daerah, sehingga implementasi green procurement di lapangan masih jauh dari ideal.
IV. Kendala Utama dalam Implementasi
Pelaksanaan green procurement di daerah menghadapi berbagai kendala yang saling terkait. Berikut adalah lima kelompok kendala utama:
A. Kapasitas Sumber Daya Manusia
Banyak instansi daerah belum memiliki pegawai pengadaan yang terlatih khusus dalam prinsip keberlanjutan. Kurangnya pemahaman mengenai Life Cycle Assessment (LCA), ecolabel, internal carbon pricing, dan Total Cost of Ownership (TCO) menyebabkan kriteria lingkungan sering diabaikan dalam dokumen lelang. Selain itu, beban kerja yang padat membuat pegawai pengadaan enggan mempelajari regulasi baru atau menyusun analisis dampak lingkungan yang memerlukan data teknis dan metodologi khusus. Tanpa pelatihan intensif dan sertifikasi kompetensi green procurement, program akan terhenti di level kebijakan tanpa terwujud di lapangan.
B. Infrastruktur dan Logistik
Produk hijau-mulai dari lampu LED hemat energi, kendaraan listrik, hingga peralatan IT bersertifikat Energy Star-tidak selalu tersedia secara merata di seluruh daerah. Banyak daerah terpencil atau luar Jawa mengalami kendala distribusi dan ketersediaan stok. Logistik untuk mengantarkan produk hijau dari pusat distribusi ke kantor kecamatan atau desa sering memerlukan biaya tambahan atau waktu lebih lama, sehingga instansi memilih opsi konvensional yang lebih murah dan mudah diperoleh. Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik juga menahan adopsi armada dinas ramah lingkungan.
C. Regulasi dan Kebijakan Lokal yang Belum Spesifik
Meskipun Perpres No. 16/2018 menyebutkan prinsip berkelanjutan dalam pengadaan, turunan regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten belum merinci kriteria ekologis yang wajib dipenuhi. Banyak peraturan daerah (Perda) terkait pengadaan masih menuliskan “memperhatikan lingkungan” secara normatif tanpa lampiran teknis ecolabel atau batas emisi. Kekosongan ini membuat pejabat pengadaan tidak memiliki dasar hukum kuat untuk menolak penawaran konvensional sekalipun tidak ramah lingkungan. Kebijakan lokal yang belum selaras dengan kebijakan nasional menciptakan celah interpretasi dan implementasi yang lemah.
D. Ketersediaan Produk Hijau dan Vendor Lokal
Pasokan produk hijau oleh vendor lokal masih terbatas. Banyak UKM di daerah belum terakreditasi ecolabel (SNI Ecolabel, FSC, Energy Star) karena biaya sertifikasi yang tinggi dan minimnya dukungan teknis. Akibatnya, vendor besar dari wilayah lain yang memiliki sertifikat lebih dominan, sehingga peluang pemberdayaan ekonomi lokal menjadi berkurang. Ketidaksiapan rantai pasok lokal menciptakan paradoks: pemerintah ingin membeli produk hijau, tetapi vendor lokal tidak masuk kualifikasi, sementara vendor nasional menyediakan produk, tetapi tidak memenuhi skema pengembangan UMKM.
E. Pembiayaan dan Insentif
Produk hijau seringkali memiliki harga awal lebih tinggi dibandingkan produk konvensional. Jika anggaran daerah tidak mengalokasikan margin untuk selisih harga, maka opsi termurah tetap menjadi pilihan default. Skema insentif fiskal atau subsidi untuk penutup selisih harga belum tersedia secara konsisten di daerah. Tanpa mekanisme dana khusus, seperti green fund atau alokasi tambahan dalam APBD untuk membeli produk bersertifikat lingkungan, unit kerja pengadaan sulit memprioritaskan produk hijau.
V. Studi Kasus Tingkat Daerah
1. Kabupaten X: Program E‑Procurement Hijau Berbasis SNI Ecolabel
Kabupaten X memulai pilot project pada 2021 dengan mewajibkan 20% dari total nilai tender pengadaan peralatan kebersihan dan perkantoran menggunakan produk bersertifikat SNI Ecolabel. Melalui kerja sama dengan BSN, pemerintah daerah memberikan pelatihan sertifikasi bagi 30 UKM lokal produsen sabun, deterjen, dan tisu daur ulang. Setelah dua tahun, capaian:
- 40% pengadaan produk kebersihan berlabel ecolabel.
- Pengurangan limbah pembersih berbahaya sebesar 25 ton/tahun.
- Peningkatan pendapatan rata-rata UKM sebesar 15%.
Namun, tantangan muncul pada tahun ketiga, ketika pasokan menjadi tidak konsisten akibat vendor lokal kewalahan memenuhi permintaan volume tinggi.
2. Kota Y: Pengadaan Kendaraan Listrik untuk Armda Dinas
Pemkot Y menargetkan 30% kendaraan dinas bertenaga listrik pada 2023-2025. Infrastruktur berupa stasiun charging dipasang di kantor-kantor OPD, dan klausul teknis dalam tender mencantumkan standar efisiensi baterai dan jarak tempuh minimal. Hasil implementasi:
- Reduksi emisi CO₂e sebesar 150 ton/tahun.
- Penurunan biaya BBM operasional 20%.
- Namun, muncul keluhan terkait jangkauan charging di area pelayanan publik, memaksa sebagian armada kembali menggunakan bahan bakar fosil.
3. Provinsi Z: Integrasi Ecolabel dalam E-Katalog
Provinsi Z menambah filter “Produk Hijau” di E-Katalog daerah, dengan daftar vendor yang telah diverifikasi ecolabel. Filter ini digunakan oleh seluruh SKPD. Hasilnya:
- Peningkatan penggunaan produk IT hemat energi bersertifikat Energy Star dari 5% menjadi 35% dalam setahun.
- Skema internal carbon pricing diterapkan untuk menilai tender besar, mempermudah opsi produk murah energi.
Namun, catatan audit menunjukkan ada vendor yang memasok produk palsu klaim, sehingga audit ketat dan blacklist vendor perlu diprioritaskan.
VI. Strategi Mitigasi dan Solusi
Mengatasi kendala implementasi green procurement di daerah memerlukan pendekatan multidimensi:
A. Penguatan Kapasitas SDM
- Pelatihan Berkelanjutan: Gelar program sertifikasi Green Procurement Officer bekerja sama dengan LKPP, BSN, dan perguruan tinggi.
- Panduan Teknis Praktis: Susun modul langkah demi langkah (SOP) untuk menyusun dokumen tender hijau, mengevaluasi ecolabel, dan menghitung TCO.
- Mentoring dan Co‑Working: Bentuk tim mentoring antar daerah-daerah pionir mendampingi daerah lain dalam 6 bulan awal implementasi.
B. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Produk
- Cluster Industri Hijau: Fasilitasi pendirian cluster UKM hijau di kawasan industri lokal dengan insentif lahan murah dan kemudahan perizinan.
- Kemitraan Kawasan: Daerah terdekat membentuk jaringan distribusi bersama untuk produk hijau, mengurangi biaya logistik.
- Market Aggregation: Pemerintah pusat atau provinsi melakukan pembelian volume besar-pool procurement-agar vendor lokal memperoleh skala ekonomi dan mampu menurunkan harga.
C. Penyusunan Kebijakan Lokal Spesifik
- Perda Green Procurement: Daerah menerbitkan Perda yang memuat fungsi ecolabel sebagai syarat administratif dan teknis, lengkap dengan lampiran jenis label dan bobot nilai.
- SOP Verifikasi: Tetapkan mekanisme audit berkala (setiap 6 bulan) oleh tim independen yang diakui untuk memastikan kebenaran ecolabel dan kelayakan vendor.
- Skor Evaluasi Lingkungan: Integrasikan skor ecolabel ke dalam sistem penilaian elektronik (SPSE lokal) agar setiap tender secara otomatis menghitung skor lingkungan.
D. Dukungan Pembiayaan dan Insentif
- Green Fund Daerah: Alokasikan 1%-2% APBD untuk subsidi selisih harga produk hijau, khususnya untuk sektor pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan).
- Tax Holiday Lokal: Berikan keringanan retribusi daerah atau PBB bagi industri hijau yang memasok produk ecolabel.
- Skema Kredit Hijau: Bekerja sama dengan perbankan syariah dan BPD untuk menyediakan kredit ringan bagi UKM yang ingin meraih sertifikasi ecolabel.
E. Penguatan Regulasi dan Pengawasan
- Sinkronisasi Perda dan Perpres: Pastikan Perda daerah merujuk Perpres 16/2018 dan pedoman LKPP, sehingga tidak ada tumpang tindih peraturan.
- Sanksi Administratif: Tetapkan denda atau blacklist bagi vendor yang terbukti melakukan klaim palsu (greenwashing).
- Reward dan Recognition: Berikan penghargaan tahunan “Daerah Berprestasi dalam Green Procurement” untuk mendorong kompetisi positif antar daerah.
VII. Rekomendasi Kebijakan dan Tindak Lanjut
- Terbitkan Peraturan Daerah (Perda) Khusus
Daerah perlu mengeluarkan Perda yang memuat kriteria ecolabel wajib untuk kategori produk strategis, skema insentif, serta mekanisme pengawasan. - Bangun Pusat Layanan Ecolabel Daerah
Sediakan satu pintu untuk layanan sertifikasi, verifikasi, dan konsultasi ecolabel bagi UKM dan vendor lokal, agar proses lebih terjangkau. - Kembangkan Modul E‑Learning Green Procurement
Modul daring yang terintegrasi dengan LMS pemerintah dapat diakses oleh pejabat pengadaan kapan saja, mengurangi beban pelatihan tatap muka. - Libatkan Akademisi dan LSM
Perguruan tinggi dapat menyusun studi kelayakan, LCA, dan indikator keberlanjutan; LSM memantau pelaksanaan dan melaporkan temuan ke publik. - Evaluasi Berkala dengan Indikator Kuantitatif
Tetapkan indikator seperti persentase belanja hijau, pengurangan emisi CO₂e, dan jumlah vendor bersertifikat, serta laporkan secara terbuka setiap semester.
VIII. Kesimpulan
Implementasi green procurement di daerah menghadapi tantangan signifikan, mulai dari kapasitas SDM yang terbatas, infrastruktur pasokan produk hijau, regulasi lokal yang belum spesifik, hingga pembiayaan dan risiko greenwashing. Namun, melalui serangkaian strategi yang terintegrasi-meliputi pelatihan intensif, pengembangan kebijakan lokal, mekanisme pendanaan khusus, serta peningkatan kapasitas rantai pasok lokal-kendala tersebut dapat diatasi. Dengan komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan semua pemangku kepentingan, green procurement akan berubah dari upaya eksperimental menjadi praktik rutin yang memadukan efisiensi anggaran, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan. Hasil akhirnya adalah daerah yang lebih tangguh, warga yang lebih sehat,dan ekosistem yang lebih terjaga bagi generasi mendatang.